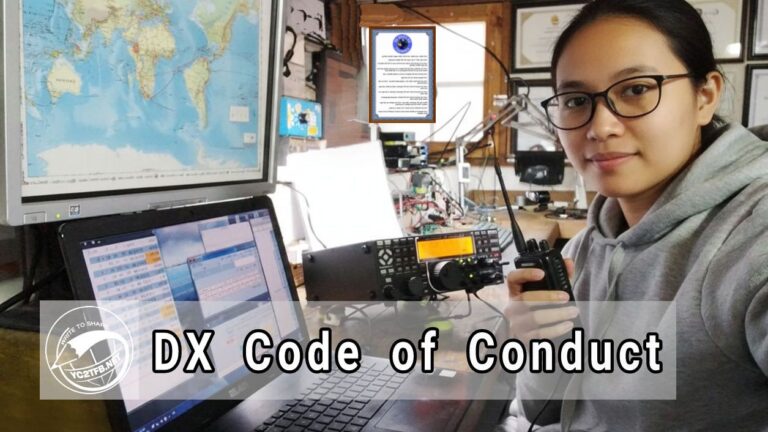ACEH Tamiang menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup parah akibat bencana alam banjir bandang, longsor, dan angin kencang. Dalam hitungan hari, kehidupan masyarakat pascabencana nyaris lumpuh. Akses jalan terputus, rumah-rumah terendam, dan rasa aman yang selama ini dijaga perlahan runtuh bersama naiknya air.
Kabar itu datang dari seorang sahabat saya, Siti Hastina Udfa, guru seni yang menetap di Dusun Bakti, Kampung Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Ia berkisah tentang kedahsyatan musibah yang bukan hanya merusak harta benda, tetapi juga mengguncang jiwa. Ia dan keluarganya ikut menjadi bagian dari deretan panjang warga terdampak.
Siti bercerita, sebelum banjir bandang datang, langit Aceh Tamiang seakan kehilangan jeda. Lima hari lima malam hujan turun tanpa henti.
Air membasahi bumi terus-menerus, seolah tak memberi kesempatan tanah untuk bernapas.
Sungai-sungai meluap, kampung tergenang, tetapi tak ada yang benar-benar menyangka bahwa bencana besar sedang mengintai.
Puncaknya terjadi pada 26 November 2025, sekitar pukul 02.30 WIB. Hujan turun disertai angin yang sangat kencang. Atap-atap rumah beterbangan, pepohonan tumbang, dan listrik mulai padam di beberapa titik.
Pagi harinya, Siti tetap berangkat bekerja. Namun, ketika ia keluar dari gang rumahnya, pemandangan tak biasa menyambut: kampung tetangga, Medang Ara, sudah tergenang air setinggi betis. Padahal, kawasan itu dikenal sebagai wilayah yang tidak pernah kebanjiran.
Ia mencoba mencari jalan alternatif, tetapi sia-sia. Air sudah masuk ke jalan utama dengan ketinggian hampir setengah meter, termasuk di depan Masjid Bukit Tempurung. Beberapa kawasan lain ikut terdampak: Kompi Senapan A di Karang Baru, perumahan BTN Satelit Graha, hingga halaman perkantoran di Aceh Tamiang.
Merasa situasi makin tak memungkinkan, Siti memutuskan pulang ke rumah, masih dengan keyakinan bahwa air akan segera surut.
Keyakinan itu runtuh pada malam harinya. Ayah Siti meminta keluarga segera mengamankan barang-barang penting. Naluri seorang tua membaca tanda-tanda alam bekerja lebih cepat. Dengan cemas dan kebingungan, Siti mulai mengepak apa saja yang bisa diselamatkan.
Sekitar pukul 20.00 WIB, ayahnya kembali meminta mereka mengungsi. Air sudah masuk ke pekarangan depan rumah, dan air itu tak lagi biasa, melainkan air banjir.
Siti, bersama ibu dan anak-anaknya, menuju salah satu balai pengajian di kampung mereka. Balai itu dipilih karena posisinya lebih tinggi dari rumah-rumah sekitar. Pengalaman banjir bandang tahun 2006 menjadi rujukan: saat itu, balai tersebut aman dari genangan.
Dengan harap-harap cemas, mereka bermalam di sana, berharap bencana kali ini tak sebesar yang dibayangkan.
Namun, pagi 27 November menyuguhkan kenyataan pahit. Ketika Siti kembali menengok rumah, air sudah setinggi satu meter di dalamnya. Ia tertegun, seakan sedang bermimpi buruk. Air mengalir deras, membawa lumpur, melumat perabot, dan kenangan.
Tangisnya pun pecah, bukan sekadar karena kehilangan, tetapi karena tak berdaya menghadapi kenyataan.
Air terus naik. Sekitar pukul 09.00 WIB ketinggiannya bertambah, dan hingga siang hari tak menunjukkan tanda-tanda surut.
Balai pengungsian yang memiliki empat anak tangga perlahan ikut terendam. Sekitar pukul 15.00 WIB, air sudah masuk ke dalam balai. Rasa takut, cemas, khawatir, dan sedih bercampur menjadi satu.
Anak-anak tak lagi bisa beristirahat dengan nyaman. Kompor dan bahan pangan terendam. Malam harinya, air di dalam balai mencapai setinggi satu meter.
Suasana pengungsian berubah mencekam. Orang-orang mulai berpikir untuk naik ke atap jika air terus meninggi.
Anak-anak panik, sebagian menangis. Pada malam Jumat itu, mereka terendam tanpa tidur, hanya berdoa agar air segera berhenti naik.
Dan Jumat, 28 November, air masih bertahan. Mereka tak tahu harus pergi ke mana lagi. Makanan nyaris tak ada. Anak-anak hanya bisa mengunyah mi instan mentah untuk menahan lapar.
Malam Sabtu adalah malam terpanjang. Pakaian lembap, tubuh lelah, perut lapar, dan tenggorokan didera dahaga.
Ada yang tertidur sambil berdiri, ada yang naik ke atap, ada pula yang duduk di dekat jendela. Anak-anak tidur sambil duduk di atas kayu yang disusun seadanya. Mereka hanya menunggu pagi, menunggu keajaiban.
Syukurlah, keajaiban itu datang perlahan. Air mulai surut, meski sangat pelan.
Hingga Sabtu malam, genangan di dalam balai mulai keluar, menyisakan lumpur tebal.
Minggu, 30 November, mereka masih bertahan di pengungsian sambil membersihkan balai agar bisa kembali ditempati. Di luar, air masih setinggi satu meter.
Setelah air mulai agak surut, Siti memutuskan bergabung dengan warga lainnya di lokasi pengungsian yang lebih besar. Di sana, ratusan orang berkumpul dengan nasib yang hampir serupa: kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan menahan lapar sambil menunggu bantuan datang.
Hari dilalui dengan sabar, duduk bersisian di ruang terbatas, berbagi cerita, berbagi keluh, dan saling menguatkan. Makanan datang dari dapur umum, sepiring nasi, lauk apa adanya.
Ketika banjir benar-benar surut, Senin, 1 Desember, Siti dan keluarganya mencoba melihat rumah. Pemandangan yang mereka dapati membuat hati hancur berkeping-keping. Banyak rumah rusak, bahkan ada yang hanyut terbawa arus. Lumpur tebal telah memasuki rumah, menutup lantai, merusak perabot, dan menyisakan bau yang menusuk. Hampir tak ada sudut rumah yang luput dari jejak banjir.
Barang-barang yang selama ini dikumpulkan bertahun-tahun rusak tak bisa diselamatkan. Namun, di tengah kehancuran itu, Siti dan keluarganya memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Mereka mulai membersihkan rumah sedikit demi sedikit, menyapu lumpur, membuang barang yang tak lagi bisa digunakan, dan menata kembali ruang seadanya.
Perlahan, kehidupan kembali dirajut. Meski jauh dari kata pulih, Siti dan keluarganya berusaha bangkit, menata hari, dan menyalakan harapan. Bencana mengajarkan tentang rapuhnya hidup, tetapi juga tentang daya tahan manusia.
Normal mungkin tak segera kembali, tetapi harapan masih terus dipupuk, dan membangun keyakinan bahwa esok bisa lebih baik.
Luka yang ditanggung Siti dan warga terdampak masih menganga. Trauma belum sepenuhnya pulih. Namun, di balik puing-puing dan air mata, harapan perlahan tumbuh. Tangan-tangan saling menguatkan, doa-doa tak putus dipanjatkan. Sebab hidup, seberat apa pun ujian yang datang, harus terus berjalan.
Penulis: Muhammad Subhan [https://www.facebook.com/share/p/1Jtp2w2QNi/]
Foto: Rumah-rumah warga terdampak banjir bandang di Dusun Bakti, Kampung Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. (Foto-Foto: Dok. Siti Hastina Udfa | Aceh Tamiang)